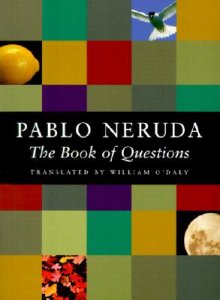Blog ini adalah daerah cagar, suaka bagi sajak-sajak, terjemahan, dan esai-esai Hasan Aspahani. Hal-ihwal yang pernah hilang dan ingin ia hapuskan.
Wednesday, June 29, 2011
[Kolom] Dari 25 Ekor Kucing,Lahir Seekor Garfield
Pencinta kucing suka Garfield,
Pembenci kucing juga suka dia.
KAUS kelas kami waktu SMA dulu bergambar karakter komik Garfield, si kucing gemuk berbulu jingga, dan tampangnya menggemaskan. Sayalah yang dipercaya kawan-kawan sekelas merancang kaus itu. Eh, bukan dipercaya, saya sebenarnya sedikit otoriter, karena saya waktu itu ketua kelas. Tentu saja waktu itu saya tak mengerti soal hak cipta, tapi saya suka Garfield, kawan sekelas saya suka juga. Rasanya, itulah kaus kelas paling keren dibandingkan dengan kaus kelas-kelas lain di angkatan kami dulu.
Saya mengenal Garfield di koran berbahasa Inggris yang dilanggani paman saya. Dia guru bahasa Inggris. Saya pada waktu SMA memang 'rakus' melahap apa saja. Termasuk mencari rujukan tentang kartun dan komik strip, karena saat itu saya bekerja di surat kabar lokal, membuat komik strip. Nama serial komik strip saya: Ketupat.
Pada saat yang sama, saya juga sangat menyukai Peanuts, komik strip karya kartunis kaya-raya Charlie M Schulz - saya entah kenapa, merasa amat kehilangan ketika beliau meninggal pada tahun 2000 lalu - dengan tokoh sekawanan anak-anak, Charlie Brown CS, dan anjingnya yang kemudian menjadi lebih terkenal daripada tuannya: Snoopy. Ketupat saya, amat dipengaruhi oleh Peanuts.
Garfield - seperti halnya Peanuts - adalah contoh nyata tentang buah lebat yang bisa kita petik jika kita menanam benih keyakinan, kerja keras, dan kreativitas. Jim Davis - begitulah James Robert Davis mencantumkan nama akrab di setiap helai karyanya - menderita asma sewaktu masih kanak-kanak. Karena itu ia banyak menghabiskan waktu di dalam rumah.
Penyakit ssmanya disebabkan alergi pada bulu hewan. Harap maklum, ayah dan ibunya adalah keluarga peternak. Rumah peternakan mereka dikepung oleh kawanan sapi, kuda, dan di dalam rumah - ini bukan hewan ternak - mereka memelihara 25 ekor kucing kampung.
Apa yang bisa dilakukan seorang anak kecil - dengan seorang saudara kandung yang sebaya - ketika harus berlama-lama di dalam rumah? Ibunda Jim memberinya pensil dan kertas. Maka menggambarlah Jim. Sebagaimana layaknya gambar anak-anak, Jim menggambar dengan anatomi yang tak becus. Ia melihat sapi, ia menggambar sapi. Tapi gambarnya tak mirip sapi. Jim kecil menambahkan tulisan: Ini sapi. Sesuatu yang sepele. Tapi, dari peristiwa kecil itu, Jim teryakinkan bahwa ketika gambar dan teks dipadukan lahir sebuah kekuatan. Dan itulah prinsip komik.
Sejak itu, dia tahu dia ingin jadi apa: dia ingin jadi kartunis. Jim kecil pun tak berhenti menggambar. Ia menggambar di mana saja, dinding, lantai, tangga, di mana saja. Berkah lain, karena betah menggambar di dalam rumah, asmanya pun berangsur pulih.
Selepas SMA, Jim masuk kolese, jurusan seni. Di situ bakatnya semakin terasah, karena fasilitas pendidikan dan buku rujuan yang lengkap. Di sana ia juga belajar drama. Di sini kita bisa belajar, betapa sarana pendidikan yang lengkap, pengajar yang baik, bisa memunculkan potensi maksimal dari anak-anak, yang kita tak tahu kelak ia akan jadi sebesar apa.
Selepas kolese, Jim magang di sebuah biro iklan. Niatnya cuma satu: bisa menjadi asisten Tom K Ryan, kartunis yang saat itu sudah berhasil dengan serial komik strip Tumbleweeds. Jim mengerjakan apa saja, menyapu lantai studio, mengepel, dan pekerjaan remeh, seperti menggambar latar dan menulis teks kartun. Pelajaran lain dari Jim, tak cukup belajar teori menggambar di perguruan tinggi, pengalaman langsung justru lebih banyak memberi pelajaran dan kelak menentukan keberhasilan Jim sebagai kartunis.
Jim pun memulai komik stripnya sendiri. Ia langsung menemukan Garfield? Tidak. Ia membuat kartun dengan tokoh kutu, Gnome Gnates. Kartun ini gagal, meskipun sudah sempat lima tahun ia berusaha untuk membesarkannya.
"Kartunmu lucu. Gambarmu bagus. Tapi, kutu? Siapa sih yang suka kutu?" kata seorang editor di sebuah perusahaan sindikat kartun. Jim menyadari kekeliruannya. Ia banting setir mencari karakter lain. Jim tidak putus asa, ia tahu, tidak ada keberhasilan yang sekali jadi. Tapi, itu tak menyurutkan tekadnya untuk terus bekerja keras.
Ia mengamati banyak kartun yang berhasil tokohnya anjing. Dan waktu itu tak ada satupun tokohnya kucing. Ia pun mulai merancang, dan Garfield baru tercipta setelah dua tahun lamanya ia mereka-reka. Ia memanggil kembali kenangan pada 25 ekor kucing yang dulu hidup bersamanya di peternakan. Nama Garfield sendiri ia pinjam dari nama kakeknya. Karakter si kakek pun dia curi: ya sikap keras kepalanya itu. Awalnya si kucing pemalas, sarkastik, sok pintar, sok filosofis itu, hanya tokoh pendamping si tokoh utama: Jon Arbukle, kartunis berwajah culun.
Menyadari potensi kebintangan pada diri Garfield, Jim memberi peran besar pada si kucing. Kartunnya langsung disambar oleh perusahaan sindikasi kartun yang sejak pertama kali terbit pada tanggal 18 Juni 1978 - wah, bulan ini sudah 33 tahun usia kemunculannya - Garfield langsung tampil di 41 koran di Amerika, di kota Boston, Dallas, dan Chicago. Jalan kesuksesan membentang di hadapan Jim yang saat itu sudah - atau baru? - berusia 33 tahun.
Popularitas Garfield lekas melejit. Pada tahun 1982, komik Garfield terbit di 1.000 surat kabar. Tahun 1987, si kucing gendut itu tampil di 2.000 surat kabar. Dan saat ini, terbit di 2,600 surat kabar di seluruh dunia. Guiness World Book of Record mengganjarinya sebagai komik strip tersindikasi paling banyak di dunia. Dibaca oleh - ditaksir secara kasar 263 juta orang setiap hari, termasuk saya yang membaca lewat lembar "Life" di surat kabar negeri Jiran The Strait Times yang saya langgani lewat kantor.
Ada satu peristiwa yang memicu - dan meyakinkan Jim - betapa dicintainya Garfield oleh para pembacanya. Beberapa bulan setelah terbit, sebuah surat kabar di Chicago menghentikan pemunculan Garfield. Apa yang terjadi? 1,300 turun ke jalan, meluruk ke kantor surat kabar tersebut, marah akibat dihentikannya komik strip itu.
Jim saat ini masih aktif menggambar. Kini, pria yang bulan Juli tanggal 28 nanti tepat berusia 67 tahun itu - mempekerjakan 50 tukang gambar, di bawah bendera perusahaan Paws, Inc. Perusahaan ini memproduksi kartun, film, serial TV, dan yang mengurusi hak cipta dan bisnis pernak-pernik barang berlogo Garfield, di Albany, negara bagian Indiana.
Kalau kepadanya ditanya bagaimana caranya menjadi kartunis yang berhasil? Ia punya jawaban begini: "...membaca, membaca, dan membaca. Untuk menjadi seniman strip-komik kau harus jadi penulis yang baik. Menguasai seni menggambar penting, tapi kemampuan menulislah yang membentuk atau menghancurkan kamu. Belajarlah apa saja, dan seberapa bisa kamu belajar," katanya.
Itu saja? Belum cukup! "Menontonlah. TV, bioskop. Bergaullah. Cari kawan, dan kegiatan. Cobalah berbagai alat gambar yang berbeda dan coba berbagai gaya. Di atas semuanya itu - milikilah sesuatu yang ingin kau sampaikan, sesuatu yang unik dan berbeda - sesuatu yang "khas" kamu," katanya.***
Labels:
kolom
Tuesday, June 28, 2011
Kita Ingin Kita Ada di Sana
TERBERKAHILAH engkau dan aku, yang memperjalankan cinta, dari hatiku ke hatimu, dan dari sebalik itu, pada waktu siang, dan juga malam.
Terberkahilah kita, karena cinta kita, adalah jalan, adalah perjalanan. Karena hati kita, adalah peta yang memandu, adalah rumah kemana menuju.
Kalau kau bertanya, kapan kita sampai? Aku jawab, seraya berjalan, kita telah sampai. Kita telah ada di tempat di mana kita ingin kita ada sana.
Terberkahilah kita, karena cinta kita, adalah jalan, adalah perjalanan. Karena hati kita, adalah peta yang memandu, adalah rumah kemana menuju.
Kalau kau bertanya, kapan kita sampai? Aku jawab, seraya berjalan, kita telah sampai. Kita telah ada di tempat di mana kita ingin kita ada sana.
Saturday, June 25, 2011
Kisah-kisah dari Seorang Sutradara dan Seorang Penulis Novel dan Tokoh-tokoh Karangan Mereka
1. Mereka Duduk Berhadap-hadapan
SEPERTI buru-buru menghabiskan minuman dan juadah yang mereka pesan. Mereka tak banyak bercakap-cakap, hanya saling tatap, lekat, tak ingin terlepaskan. Mereka duduk di sudut yang tak langsung tampak dari tempat sang sutradara dan penulis novel yang tengah menulis berhadap-hadapan.
"Ayolah, waktu kita tak banyak. Kita harus segera kembali ke dalam kisah yang mereka tuliskan. Kau ke skenario itu, dan aku ke novel itu," kata si lelaki. Si perempuan menurut, dengan sangat enggan, ia habiskan tegukan terakhir minumannya, dan ia tandaskan suapan terakhir juadahnya.
2. Hei, Siapa ini yang Tersesat?
TIBA-TIBA si Penulis Novel berteriak. "Hei!?"
Ada seorang yang tidak ia kenal, tiba-tiba hadir dalam adegan yang ia tulis, dia yang sejak awal tak ada dalam kisah yang sedang ia tulis.
"Apa ciri-cirinya?" tanya Si Sutradara. Si Penulis Novel menyenaraikan ciri-ciri si karakter yang tersesat ke dalam kisahnya.
"Sepertinya aku pernah membayangkannya, tapi ia nanti akan hadir di bagian-bagian akhir skenario yang sedang kutuls ini," kata Si Sutradara.
3. Tidak Ada yang Tahu tentang Dua Keinginan Itu
SETELAH satu jam duduk menulis berhadap-hadapan, Si Sutradara menyelesaikan 15 halaman skenario dan Si Penulis Novel menuntaskan lima halaman. Si tokoh perempuan dalam skenario itu merasa telah menghabiskan setengah masa hidupnya. Si tokoh lelaki dalam novel itu merasa hidupnya masih berputar di situ-situ saja.
Kedua tokoh itu, ingin sekali di akhir cerita mereka bertemu, lalu bebas dari belenggu kedua cerita, dan menjalani takdir kisah mereka sendiri. Si Sutradara dan si Penulis Skenario tentu saja tidak tahu keinginan kedua tokoh itu.
SEPERTI buru-buru menghabiskan minuman dan juadah yang mereka pesan. Mereka tak banyak bercakap-cakap, hanya saling tatap, lekat, tak ingin terlepaskan. Mereka duduk di sudut yang tak langsung tampak dari tempat sang sutradara dan penulis novel yang tengah menulis berhadap-hadapan.
"Ayolah, waktu kita tak banyak. Kita harus segera kembali ke dalam kisah yang mereka tuliskan. Kau ke skenario itu, dan aku ke novel itu," kata si lelaki. Si perempuan menurut, dengan sangat enggan, ia habiskan tegukan terakhir minumannya, dan ia tandaskan suapan terakhir juadahnya.
2. Hei, Siapa ini yang Tersesat?
TIBA-TIBA si Penulis Novel berteriak. "Hei!?"
Ada seorang yang tidak ia kenal, tiba-tiba hadir dalam adegan yang ia tulis, dia yang sejak awal tak ada dalam kisah yang sedang ia tulis.
"Apa ciri-cirinya?" tanya Si Sutradara. Si Penulis Novel menyenaraikan ciri-ciri si karakter yang tersesat ke dalam kisahnya.
"Sepertinya aku pernah membayangkannya, tapi ia nanti akan hadir di bagian-bagian akhir skenario yang sedang kutuls ini," kata Si Sutradara.
3. Tidak Ada yang Tahu tentang Dua Keinginan Itu
SETELAH satu jam duduk menulis berhadap-hadapan, Si Sutradara menyelesaikan 15 halaman skenario dan Si Penulis Novel menuntaskan lima halaman. Si tokoh perempuan dalam skenario itu merasa telah menghabiskan setengah masa hidupnya. Si tokoh lelaki dalam novel itu merasa hidupnya masih berputar di situ-situ saja.
Kedua tokoh itu, ingin sekali di akhir cerita mereka bertemu, lalu bebas dari belenggu kedua cerita, dan menjalani takdir kisah mereka sendiri. Si Sutradara dan si Penulis Skenario tentu saja tidak tahu keinginan kedua tokoh itu.
Friday, June 24, 2011
[Ruang Renung #253] Apa yang Memeristiwa pada Kita
Bagaimana memulai langkah menulis puisi? Hayatilah hidupmu. Sadarilah setiap hal kecil yang memeristiwa padamu. Banyak sekali peristiwa di sekitarmu, bukan? Nyala lampu jatuh di jalan. Sudut buku yang terlipat. Gelas yang belum terisi. Telepon genggam yang kehabisan daya baterei.
Peristiwa-peristiwa itu, kau rebutlah, jadikan itu bagian dari dirimu, atau jadikan dirimu bagian dari peristiwa itu. Peristiwa itu memperkaya hidupmu. Lalu banyak hal bisa kau ucapkan. Tak habis-habis. Itulah saatnya kau mencari cara ucap: memuisi. Ayo, sadari peristiwa yang memeristiwa padamu! Tuliskan. Tuliskan. Itu akan jadi bahan subur bagi puisi-puisi!
Peristiwa-peristiwa itu, kau rebutlah, jadikan itu bagian dari dirimu, atau jadikan dirimu bagian dari peristiwa itu. Peristiwa itu memperkaya hidupmu. Lalu banyak hal bisa kau ucapkan. Tak habis-habis. Itulah saatnya kau mencari cara ucap: memuisi. Ayo, sadari peristiwa yang memeristiwa padamu! Tuliskan. Tuliskan. Itu akan jadi bahan subur bagi puisi-puisi!
Labels:
Ruang Renung
[Ruang Renung #252] Dalam Setangkai Sajak
DALAM setangkai sajak tidak semua kata adalah bunga. Ada kelopak, daun, mahkota, berkas embun yg mengering. Kita penata dan perangkainya.
DALAM setangkai sajak, tak selalu adalah bunga. Kadang tiadalah bunga atau bunga yg menyaran adanya justru menguatkan kesajakannya.
DALAM setangkai sajak, kadang kau tak harus memetik bunga kata, biarkan dia mekar dan melayu dan jatuh dari pokoknya.
DALAM setangkai sajak, tak selalu adalah bunga. Kadang tiadalah bunga atau bunga yg menyaran adanya justru menguatkan kesajakannya.
DALAM setangkai sajak, kadang kau tak harus memetik bunga kata, biarkan dia mekar dan melayu dan jatuh dari pokoknya.
Labels:
Ruang Renung
Kau Datang Membawa Berbagai Cerita
CERITA dengan adegan kau dan aku, tanpa sutradara. Dan kita
salah tingkah, bagai ada ratusan kamera, sembunyi, merekam kita.
Dan aku tiba-tiba menjadi penyair, menulis sajak-sajak. Gagap
kita membacanya. Kita seperti sama-sama baru belajar aksara.
Cerita dengan tanda-seru di setiap akhir kalimatnya. Ya,
di usia semekar saat itu, kita tak mengenal tanda-tanya.
"Wahai, para Ahli Bahasa, kalian harus membuat tanda-senyum
untuk kisah-kisah kecil kami," aku berseru, dan kau tertawa.
salah tingkah, bagai ada ratusan kamera, sembunyi, merekam kita.
Dan aku tiba-tiba menjadi penyair, menulis sajak-sajak. Gagap
kita membacanya. Kita seperti sama-sama baru belajar aksara.
Cerita dengan tanda-seru di setiap akhir kalimatnya. Ya,
di usia semekar saat itu, kita tak mengenal tanda-tanya.
"Wahai, para Ahli Bahasa, kalian harus membuat tanda-senyum
untuk kisah-kisah kecil kami," aku berseru, dan kau tertawa.
Wednesday, June 22, 2011
Holandia dalam Ingatan
Sajak Hendrik Marsman
Mengenang Holandia
Aku melihat sungai-sungai membentang
meliuk menembusi, tak terbilang
hamparan, tanah yang merendah,
barisan pohon poplar
memarkahi kakilangit,
di sana nyaris tiada kutemukan kata
tegak ringan bagai bulu hiasan;
dan kekal-mengekallah
dalam keluasan
negeri petani -
menyandar ke hamparan
desa-desa, riungan pepohonan,
penggal pucuk menara kecil
gereja dan pohon elma
dalam rancangan kehijauan.
Udara menggantung rendah
dan matahari perlahan
tertutup dalam lembab kabut
mengelabu - menyeteru - membancuh
dan di setiap distrik
gemuruh suara air itu
bencana yang tak berakhiran itu
terdengar, mencekamkan.
Mengenang Holandia
Aku melihat sungai-sungai membentang
meliuk menembusi, tak terbilang
hamparan, tanah yang merendah,
barisan pohon poplar
memarkahi kakilangit,
di sana nyaris tiada kutemukan kata
tegak ringan bagai bulu hiasan;
dan kekal-mengekallah
dalam keluasan
negeri petani -
menyandar ke hamparan
desa-desa, riungan pepohonan,
penggal pucuk menara kecil
gereja dan pohon elma
dalam rancangan kehijauan.
Udara menggantung rendah
dan matahari perlahan
tertutup dalam lembab kabut
mengelabu - menyeteru - membancuh
dan di setiap distrik
gemuruh suara air itu
bencana yang tak berakhiran itu
terdengar, mencekamkan.
[Kolom] Ketut Namanya, Ia Kawan Saya
DARI dia saya belajar banyak tentang keberanian, kerendahhatian, ketulusan, kesetiakawanan, dan toleransi. Tanpa khotbah, tanpa ceramah. Ia mengajarkan dengan perilakunya. Saya belajar dari apa yang dengan rendah hati ia kerjakan.
Kami berkawan sejak saya bekerja di sebuah perusahaan kehutanan di utara Kalimantan, dia sudah lebih dahulu bekerja di situ. Saya staf junior, dia manajer senior, meski kami berbeda bagian. Saya di bagian penelitian dan pengembangan, dia di departemen teknik sipil. Saya masih lajang yang sedang sangat ketat menabung untuk biaya menikah, dia sudah beranak seorang. Perkawanan kami terjalin karena di kota itu kami sama-sama pendatang. Tak ada sanak tak ada saudara.
Kami merasa senasib dan meski tentu saya tak sebanding dengan kekayaan pengalamannya, kami sering menemukan kesamaan. Dia sejak kecil hidup terpisah dari orangtua. “Saya tinggal di rumah nenek,” katanya. Di situ, dia sudah belajar mandiri. Menimba dan memikul air, memelihara sapi, dan pergi sekolah belasan kilometer berjalan kaki. Jejak-jejak kerja keras tampak memancar dari pribadinya. “Kalau saya cerita, istri dan anak saya bisa menangis,” katanya. Tapi, ia mengakui, ada satu perilaku “buruk” yang ia punya sejak kecil: ia suka menyabung ayam.
“Makanya bapak malu dan saya ‘diusir’,” katanya. Dia dikirim untuk sekolah SMA di Lombok, menyeberang ke timur dari Bali. Selama di pulau itu, kecuali jika ada upacara adat di Karangasem, kampungnya di Bali, dia tak pernah pulang. “Kalau libur saya main, sampai ke Timor,” ujarnya.
Tamat SMA dia kembali ke Denpasar dan kuliah di sana dengan biaya yang ia cari sendiri. Tamat kuliah, dengan gelar sarjana ia menaklukkan Jakarta. Ikut banyak proyek membangun gedung-gedung besar (ia menyebut beberapa gedung yang menjadi landmark ibukota - dan lama tidur di pura, di Taman Mini Indonesia Indah. “Saya ini avonturir,” katanya, dengan pengucapan “t” khas lidah orang Bali. Semangat pertualangan itulah yang membawanya sampai ke Kalimantan dan mempertemukan kami.
*
Ada masa-masa ketika krisis menghantam juga perusahaan tempat kami sama-sama bekerja itu. Saya sudah menikah, dan tak melihat ada masa depan lagi di perusahaan itu. Anggaran litbang tak pernah lagi turun. Saya nyaris tak punya sesuatu untuk dikerjakan, dan membantu bagian lain.
Mungkin sayalah orang pertama yang berhenti bekerja di sana. Lagi pula, saya kemudian menyadari bahwa kerja di hutan bukanlah bidang saya. Saya ingin kembali menjadi wartawan. Ketika awal bulan lalu, saya bertemu dia di Denpasar, saya baru tahu, dialah orang terakhir yang bertahan sampai perusahaan itu benar-benar tutup.
“Waktu itu saya merangkap banyak kerjaan. Manajer keuangan, manajer personalia, manajer umum. Semua mengundurkan diri,” katanya. Dia bertahan, dan itu artinya dia harus menghadapi karyawan yang berdemo, kontraktor yang menagih bayaran pekerjaan, dan gugatan soal lahan dari penduduk asli di sekitar hutan. Saya malu, sementara saya lebih dahulu “melarikan diri”, cari selamat sendiri, kawan saya ini justru memilih bertahan dan menyelesaikan satu per satu persoalan perusahaan sampai perusahaan tutup.
*
Di Bali, kampung halamannya, dia sempat mengelola koperasi. Ia besarkan koperasi itu hingga beranggota ribuan orang dan bisa memutar modal ratusan miliar. Koperasi itu – akibat disangkut-sangkutkan dengan kepentingan politik banyak orang besar - “diganggu” dengan alasan melanggar undang-undang perbankan – tuduhan yang tak pernah bisa dibuktikan – koperasi itu digerebek, disita asetnya, dan penanganan kasusnya tak selesai, dan berlarut-larut. Ia mundur.
“Padahal, ini koperasi dapat ISO sebagai bukti manajemen kami baik,” katanya. Ia kecewa dengan banyak hal di negeri ini. Tapi ia tak pernah mau berhenti. Ia tidak menyerah tapi memilih menyingkir dari pusaran masalah. Ia kemudian mendirikan perusahaan properti sendiri, menyewa ruang kantor, dan mengembangkan banyak usaha – dari cucian mobil, toko obat, sampai rencana membuka perkebunan kacang tanah - yang mempekerjakan banyak orang.
“Saya banyak kawan. Banyak yang percaya. Saya jaga kepercayaan orang lain,” katanya. Selama bertamu di kantornya, saya ikut menemani dia bertemu dengan beberapa mitra yang percaya memberikan modal miliaran kepadanya, untuk berbagai usaha.
*
Di Tarakan, kami sering berbincang soal masa depan republik ini. Ini perbincangan orang yang peduli. Televisi sedang gencar menyiarkan kerusuhan demi kerusuhan di Jakarta. Mei 1998. Di televisi kantor, kami sama-sama menonton Suharto saat penguasa 32 tahun itu berpidato, menyatakan berhenti. Kami sadar tak akan bisa berbuat banyak, kecuali apa yang kami bisa lakukan dengan dua tangan kami sendiri. Tapi, setidaknya kami peduli. Setidaknya kami menyadari apa perubahan besar yang sedang terjadi di negeri ini. Perusahaan kami, sejak awal sudah dijangkiti bibit penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mendapatkan lahan, si pemodal mendudukan salah satu anak Suharto menjadi komisaris, tentu dengan saham kosong.
*
“Oktober nanti, kami akan ke Tarakan,” katanya. Ia menyebut kota di mana perusahaan kami dulu beroperasi. Di sana, rupanya ia punya “warisan”. Ada penduduk setempat yang menganggapnya sudah seperti anak sendiri. Di Tarakan, yang kami sepakati tak ada ikan bakar dan bakso seenak yang ada di kota itu - setiap pagi si bapak angkat mengantarkan ikan atau udang segar.
Kelak, kawan saya mengongkosi bapak angkatnya itu menunaikan ibadah haji. Dia tak bisa datang melepas si bapak angkat berangkat ke tanah suci. “Di sana mereka kenduri dan berdoa, saya di Bali berdoa juga dengan cara saya di sini. Pokoknya, pergi selamat, pulang selamat. Kan begitu?” katanya.
“Beliau sudah meninggal. Anak-anaknya minta saya datang karena ada wasiat dari Pak Gaek,” katanya menyebut nama orang yang ia bapakkan. Pak Gaek meninggalkan sejumlah sertifikat tanah, dan tanah itu tidak boleh dibagi sebelum kawan saya itu lebih dahulu memilih salah satunya. Toleransi, kawan saya itu tidak sekadar mempercakapkannya. Ia benar-benar mengamalkannya.
*
Di Bali, dia menjadi pemandu wisata saya. Di sela-sela Kongres SPS yang saya hadiri, kami mencuri waktu. Ia mengantar saya ke Sanur, ke cabang Joger di Luwus, dan ke Ubud, kecamatan yang paling terkenal di dunia. Ia tunjukkan di mana tempat pengambilan gambar film “Eat, Pray, Love” yang dibintangi Julia Robert. Kami menelusuri jalan-jalan ke puncak Ubud, dengan sawah-sawah tertata amat rapi di kiri-kanannya. Sepanjang perjalanan saya dapat pelajaran tentang hal lain: betapa ia peduli dengan alam dan budaya.
“Kita sudah tua, apa yang terbaik bisa kita wariskan untuk anak cucu? Alam yang terjaga. Saya sekarang sedang bekerja untuk menyelamatkan mata air. Banyak yang salah dari cara pemerintah di Bali ini mengelola alam, terutama mata air. Padahal itulah sumber utama kehidupan. Kalau mata air rusak, semuanya pasti ikut rusak,” katanya. Setidaknya, setiap minggu, dia akan mendatangi satu mata air. Melihat keadaannya, mendata. Jika ada yang salah di sekitar mata air itu, dia akan bergerak.
Anak lelakinya, yang bercita-cita jadi dokter, adalah penari Bali yang hebat. “Saya belikan satu set gamelan. Saya bahagia karena anak saya yang masih SMA itu mau mendalami budaya tradisional. Saya tak menyuruh dia. Tapi dia sadar, Bali ini kekuatan dan kekayaannya adalah budaya. Kalau tak ada yang meneruskan itu, Bali ini tak ada apa-apanya lagi,” katanya. Kawan saya itu, sebut saja ia: Ketut namanya. []
Kami berkawan sejak saya bekerja di sebuah perusahaan kehutanan di utara Kalimantan, dia sudah lebih dahulu bekerja di situ. Saya staf junior, dia manajer senior, meski kami berbeda bagian. Saya di bagian penelitian dan pengembangan, dia di departemen teknik sipil. Saya masih lajang yang sedang sangat ketat menabung untuk biaya menikah, dia sudah beranak seorang. Perkawanan kami terjalin karena di kota itu kami sama-sama pendatang. Tak ada sanak tak ada saudara.
Kami merasa senasib dan meski tentu saya tak sebanding dengan kekayaan pengalamannya, kami sering menemukan kesamaan. Dia sejak kecil hidup terpisah dari orangtua. “Saya tinggal di rumah nenek,” katanya. Di situ, dia sudah belajar mandiri. Menimba dan memikul air, memelihara sapi, dan pergi sekolah belasan kilometer berjalan kaki. Jejak-jejak kerja keras tampak memancar dari pribadinya. “Kalau saya cerita, istri dan anak saya bisa menangis,” katanya. Tapi, ia mengakui, ada satu perilaku “buruk” yang ia punya sejak kecil: ia suka menyabung ayam.
“Makanya bapak malu dan saya ‘diusir’,” katanya. Dia dikirim untuk sekolah SMA di Lombok, menyeberang ke timur dari Bali. Selama di pulau itu, kecuali jika ada upacara adat di Karangasem, kampungnya di Bali, dia tak pernah pulang. “Kalau libur saya main, sampai ke Timor,” ujarnya.
Tamat SMA dia kembali ke Denpasar dan kuliah di sana dengan biaya yang ia cari sendiri. Tamat kuliah, dengan gelar sarjana ia menaklukkan Jakarta. Ikut banyak proyek membangun gedung-gedung besar (ia menyebut beberapa gedung yang menjadi landmark ibukota - dan lama tidur di pura, di Taman Mini Indonesia Indah. “Saya ini avonturir,” katanya, dengan pengucapan “t” khas lidah orang Bali. Semangat pertualangan itulah yang membawanya sampai ke Kalimantan dan mempertemukan kami.
*
Ada masa-masa ketika krisis menghantam juga perusahaan tempat kami sama-sama bekerja itu. Saya sudah menikah, dan tak melihat ada masa depan lagi di perusahaan itu. Anggaran litbang tak pernah lagi turun. Saya nyaris tak punya sesuatu untuk dikerjakan, dan membantu bagian lain.
Mungkin sayalah orang pertama yang berhenti bekerja di sana. Lagi pula, saya kemudian menyadari bahwa kerja di hutan bukanlah bidang saya. Saya ingin kembali menjadi wartawan. Ketika awal bulan lalu, saya bertemu dia di Denpasar, saya baru tahu, dialah orang terakhir yang bertahan sampai perusahaan itu benar-benar tutup.
“Waktu itu saya merangkap banyak kerjaan. Manajer keuangan, manajer personalia, manajer umum. Semua mengundurkan diri,” katanya. Dia bertahan, dan itu artinya dia harus menghadapi karyawan yang berdemo, kontraktor yang menagih bayaran pekerjaan, dan gugatan soal lahan dari penduduk asli di sekitar hutan. Saya malu, sementara saya lebih dahulu “melarikan diri”, cari selamat sendiri, kawan saya ini justru memilih bertahan dan menyelesaikan satu per satu persoalan perusahaan sampai perusahaan tutup.
*
Di Bali, kampung halamannya, dia sempat mengelola koperasi. Ia besarkan koperasi itu hingga beranggota ribuan orang dan bisa memutar modal ratusan miliar. Koperasi itu – akibat disangkut-sangkutkan dengan kepentingan politik banyak orang besar - “diganggu” dengan alasan melanggar undang-undang perbankan – tuduhan yang tak pernah bisa dibuktikan – koperasi itu digerebek, disita asetnya, dan penanganan kasusnya tak selesai, dan berlarut-larut. Ia mundur.
“Padahal, ini koperasi dapat ISO sebagai bukti manajemen kami baik,” katanya. Ia kecewa dengan banyak hal di negeri ini. Tapi ia tak pernah mau berhenti. Ia tidak menyerah tapi memilih menyingkir dari pusaran masalah. Ia kemudian mendirikan perusahaan properti sendiri, menyewa ruang kantor, dan mengembangkan banyak usaha – dari cucian mobil, toko obat, sampai rencana membuka perkebunan kacang tanah - yang mempekerjakan banyak orang.
“Saya banyak kawan. Banyak yang percaya. Saya jaga kepercayaan orang lain,” katanya. Selama bertamu di kantornya, saya ikut menemani dia bertemu dengan beberapa mitra yang percaya memberikan modal miliaran kepadanya, untuk berbagai usaha.
*
Di Tarakan, kami sering berbincang soal masa depan republik ini. Ini perbincangan orang yang peduli. Televisi sedang gencar menyiarkan kerusuhan demi kerusuhan di Jakarta. Mei 1998. Di televisi kantor, kami sama-sama menonton Suharto saat penguasa 32 tahun itu berpidato, menyatakan berhenti. Kami sadar tak akan bisa berbuat banyak, kecuali apa yang kami bisa lakukan dengan dua tangan kami sendiri. Tapi, setidaknya kami peduli. Setidaknya kami menyadari apa perubahan besar yang sedang terjadi di negeri ini. Perusahaan kami, sejak awal sudah dijangkiti bibit penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mendapatkan lahan, si pemodal mendudukan salah satu anak Suharto menjadi komisaris, tentu dengan saham kosong.
*
“Oktober nanti, kami akan ke Tarakan,” katanya. Ia menyebut kota di mana perusahaan kami dulu beroperasi. Di sana, rupanya ia punya “warisan”. Ada penduduk setempat yang menganggapnya sudah seperti anak sendiri. Di Tarakan, yang kami sepakati tak ada ikan bakar dan bakso seenak yang ada di kota itu - setiap pagi si bapak angkat mengantarkan ikan atau udang segar.
Kelak, kawan saya mengongkosi bapak angkatnya itu menunaikan ibadah haji. Dia tak bisa datang melepas si bapak angkat berangkat ke tanah suci. “Di sana mereka kenduri dan berdoa, saya di Bali berdoa juga dengan cara saya di sini. Pokoknya, pergi selamat, pulang selamat. Kan begitu?” katanya.
“Beliau sudah meninggal. Anak-anaknya minta saya datang karena ada wasiat dari Pak Gaek,” katanya menyebut nama orang yang ia bapakkan. Pak Gaek meninggalkan sejumlah sertifikat tanah, dan tanah itu tidak boleh dibagi sebelum kawan saya itu lebih dahulu memilih salah satunya. Toleransi, kawan saya itu tidak sekadar mempercakapkannya. Ia benar-benar mengamalkannya.
*
Di Bali, dia menjadi pemandu wisata saya. Di sela-sela Kongres SPS yang saya hadiri, kami mencuri waktu. Ia mengantar saya ke Sanur, ke cabang Joger di Luwus, dan ke Ubud, kecamatan yang paling terkenal di dunia. Ia tunjukkan di mana tempat pengambilan gambar film “Eat, Pray, Love” yang dibintangi Julia Robert. Kami menelusuri jalan-jalan ke puncak Ubud, dengan sawah-sawah tertata amat rapi di kiri-kanannya. Sepanjang perjalanan saya dapat pelajaran tentang hal lain: betapa ia peduli dengan alam dan budaya.
“Kita sudah tua, apa yang terbaik bisa kita wariskan untuk anak cucu? Alam yang terjaga. Saya sekarang sedang bekerja untuk menyelamatkan mata air. Banyak yang salah dari cara pemerintah di Bali ini mengelola alam, terutama mata air. Padahal itulah sumber utama kehidupan. Kalau mata air rusak, semuanya pasti ikut rusak,” katanya. Setidaknya, setiap minggu, dia akan mendatangi satu mata air. Melihat keadaannya, mendata. Jika ada yang salah di sekitar mata air itu, dia akan bergerak.
Anak lelakinya, yang bercita-cita jadi dokter, adalah penari Bali yang hebat. “Saya belikan satu set gamelan. Saya bahagia karena anak saya yang masih SMA itu mau mendalami budaya tradisional. Saya tak menyuruh dia. Tapi dia sadar, Bali ini kekuatan dan kekayaannya adalah budaya. Kalau tak ada yang meneruskan itu, Bali ini tak ada apa-apanya lagi,” katanya. Kawan saya itu, sebut saja ia: Ketut namanya. []
Labels:
kolom
Tuesday, June 21, 2011
Dua Sekawan
Sajak Hendrik Marsman
BULAN menghamparkan gurun salju, di padang malam.
Lelaki, kepada kawan sekawan, mengisahkan hidupnya:
Keajaiban rebut tempat, mendengarkan ini percakapan:
hati mereka telah bagai mendua, sama bersama jalan
Hati yang seorang sesekali menoleh kebelakang
Berkata ke hati sendiri: tapi aku tak seperti itu?
Perempuan; lain perempuan; yang tiada, habis menyita
seperti, itu seperti akhir dari segala yang segala:
Hati yang seorang meneruskan, yang lain tinggal diam,
tapi tak satu menemu Surga, dalam langkah bersendirian.
BULAN menghamparkan gurun salju, di padang malam.
Lelaki, kepada kawan sekawan, mengisahkan hidupnya:
Keajaiban rebut tempat, mendengarkan ini percakapan:
hati mereka telah bagai mendua, sama bersama jalan
Hati yang seorang sesekali menoleh kebelakang
Berkata ke hati sendiri: tapi aku tak seperti itu?
Perempuan; lain perempuan; yang tiada, habis menyita
seperti, itu seperti akhir dari segala yang segala:
Hati yang seorang meneruskan, yang lain tinggal diam,
tapi tak satu menemu Surga, dalam langkah bersendirian.
Teluk Dipeluk Senja
Sajak Hendrik Marsman
Senja tiba.
Bulan besar, bulan yang merah
perlahan terambang dari garis gelombang
di gigir ketimuran
dipeluk teluk senja, nyaris tiada bernafas.
Mimpi membonceng pada gelombang
Menampak padaku yang berbeban segala hal-ihwal,
yang tak terhasratkan, bertahun dalam ragu, aku bergelut merebut,
kukira kebahagiaan mesti dipertanyakan
dan hidup tanpa derita, apa ada harganya.
O, betapa ini menakjubkan, bertahan
dalam gempuran keraguan ini!
dalam lindapan kenaungan palma malam
Aku terasuk damai, terasuk tenteram.
Senja tiba.
Bulan besar, bulan yang merah
perlahan terambang dari garis gelombang
di gigir ketimuran
dipeluk teluk senja, nyaris tiada bernafas.
Mimpi membonceng pada gelombang
Menampak padaku yang berbeban segala hal-ihwal,
yang tak terhasratkan, bertahun dalam ragu, aku bergelut merebut,
kukira kebahagiaan mesti dipertanyakan
dan hidup tanpa derita, apa ada harganya.
O, betapa ini menakjubkan, bertahan
dalam gempuran keraguan ini!
dalam lindapan kenaungan palma malam
Aku terasuk damai, terasuk tenteram.
Saturday, June 18, 2011
Di Chiang Kai Sek Memorial Taipei
AKU tak tahu mana pintu ke perpustakaan itu
hingga ke jenjang akhir dari 89 anak tanggamu
Aku terengah membaca, nama-nama penguasa,
keluar masuk pintu penjara, pintu istana negara
hingga ke jenjang akhir dari 89 anak tanggamu
Aku terengah membaca, nama-nama penguasa,
keluar masuk pintu penjara, pintu istana negara
Lihat Kebunku Penuh dengan Luka
Thursday, June 16, 2011
Hanya Selewat Siluet
INI hanya ada sedikit saja cahaya, dari muka
dan kau menghalangi aku dari terus terang itu
Hanya sedikit cahaya, mengguntingi bayangan,
melakar siluet kita, menghitamkan kenangan
Hanya cahaya bertahan dari padam, dan kita
yang tak bersapaan, tapi tak saling ingin,
juga tiada alasan untuk saling meninggalkan
dan kau menghalangi aku dari terus terang itu
Hanya sedikit cahaya, mengguntingi bayangan,
melakar siluet kita, menghitamkan kenangan
Hanya cahaya bertahan dari padam, dan kita
yang tak bersapaan, tapi tak saling ingin,
juga tiada alasan untuk saling meninggalkan
Wednesday, June 15, 2011
[Kolom] Ia Memberdayakan 300 Pengrajin
SEBELUM ia membangun usahanya sendiri, enam tahun dia bekerja di bank, pada bagian kredit. Dengan masa kerja selama itu, tentu dia tahu seluk-beluk perbankan. Tapi dia sampai hari ini, tetap menjalankan bisnisnya sebagai “bisnis rumahan”, ia tak mau memakai jasa bank untuk mengembangkan usahanya.
Ia kenal dan dikenal dengan baik oleh kalangan bank di Bali. Ia nasabah yang baik, dan sudah banyak terima tawaran kredit. Ia tak pernah manfaatkan tawaran itu. Sebuah bank bahkan memberi fasilitas kredit siaga, sebesar Rp1 miliar. Dana sebesar itu dicatatkan atas namanya dan bisa dipakai kapanpun jika ia perlu. “Tak ada biaya, dan tak ada bunga.Kalau saya pakai, baru nanti kena bunga. Tapi, saya mau pakai buat apa?” katanya.
Pekan lalu dia menjemput saya di Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Ini pertemuan pertama kali setelah berpisah tujuh belas tahun lalu. Kami kuliah di universitas yang sama, angkatan sama, jurusan yang sama. Ia tergolong tekun, pintar, rajin, dan bersama beberapa kawan ia diwisuda lebih dahulu daripada rata-rata kami. Sejak itu kami tidak pernah bertemu. Secara fisik, ia tak banyak berubah. Ia pun tetap saja sederhana seperti saya mengenalnya dulu. Ponselnya dari kelas yang harganya tak sampai Rp200 ribu. Saya yang nyaris tak ia kenali. “Kamu gemuk,” katanya. Ya, tentu saja, di tahun-tahun kuliah saya menu tetap saya: tempe sayur sepotong, nasih putih, kecap yang banyak (gratis), dan lalap plus sambal (gratis). Harganya waktu itu Rp350.
Sewaktu kuliah dulu, bersama Yana – yang kini jadi istri saya - kami sama-sama mengelola majalah jurusan. Humus namanya. Nama yang diambil dari kuliah Dasar-dasar Ilmu Tanah. Humus adalah bentuk akhir dari pelapukan bahan organik, di mana mineral-mineralnya bisa diserap dengan mudah oleh tumbuhan. Humus, secara organik menyuburkan tanah.
Ada malam-malam kami habiskan di rental komputer, mengetik naskah untuk majalah dan menata perwajahan halaman-halamannya. Itu yang mengakrabkan kami. Ia berasal dari Tasik, dan sebagai orang Sunda yang baik dia tentu saja susah membedakan huruf dengan bunyi labial “p”, dan labiodental “v”, dan “f”. Ia pernah marah karena kami tertawa ketika dia bertanya, “Eh, ‘stap’ itu ngetiknya pakai ‘pe’ atau pakai ‘ep’?”
*
“Kerja di bank itu berat. Target tinggi,” katanya. Ia sempat berpindah kerja di dua bank swasta. Di bank kedua - ini yang ia syukuri - selama setahun lebih ia mendapat pelatihan soal seluk-beluk bisnis dan keuangan. Bagi kami yang dari Fakultas Pertanian, tentu itu ilmu baru.
Di bagian kredit, ia harus menyalurkan sejumlah besar dana nasabah. Targetnya gila-gilaan, katanya, tapi tetap saja itu harus dilakukan dengan sangat berhat-hati, sesuai azas kehati-hatian perbankan. “Berangkat kerja sudah stres. Mau sampai kantor tambah stres. Di kantor lebih stres lagi,” katanya.
Ia mulai berpikir membangun usahanya sendiri. Di kampungnya, banyak pengrajin barang-barang cindera mata yang pasarnya terbatas. Barangnya bagus-bagus. Desainnya khas. Dan jarang ada daerah lain yang memproduksi. Ia melihat peluang di situ. Ia berpikir untuk memasarkannya di tempat di mana arus turis tak putus sepanjang tahun: Bali.
“Saya mulai dulu pakai motor. Keranjang kiri kanan penuh sandal buatan Tasik,” katanya. Kalau saya ketemu dia saat itu, katanya, pasti saya tak percaya dan tak kenal. “Saya titip ke toko-toko, ke kios-kios di Sanur, Kuta, Denpasar,” katanya. Bali sama sekali asing buat dia. Ketika pertama kali mendengar dia ada di Bali, dan skala usahanya sudah besar, saya heran. Ketika bertemu, saya tanyakan itu. “Kok bisa terpikir berbisnis di Bali?” tanya saya. “Ya, coba-coba aja…” katanya.
Sepanjang perjalanan dari mobil ke rumahnya di kawasan Jimbaran, saya mengorek banyak pelajaran bisnis dari dia. Kawan saya ini menjaga hubungan sangat baik dengan pengrajin di kampungnya di Tasik. Ia menyeleksi dari beberapa, hingga sekarang punya tujuh kelompok pengrajin dengan jumlah pengraji tiga ratus orang lebih.
“Mereka saya minta hanya menyalurkan hasilnya hanya lewat saya. Beberapa desain dari saya, sesuai kebutuhan turis di Bali sini. Saya bayar kontan ke mereka.Uang saya kirim, mereka terima baru barang dikirim,” katanya.
Dengan cara itu, para pengrajin selalu punya dana untuk berproduksi. “Kalau ada yang minta pinjam uang untuk produksi, berarti ada yang tidak beres dari cara dia mengelola keuangan. Saya tak mau pakai lagi pengrajin yang begitu. Saya tahu berapa keuntungan mereka, dan berapa biaya produksi,” kata kawan saya. Ia dan para pengrajin memakai telepon selular dari satu operator yang sama. “Ini syarat penting kalau mau kerja sama dengan saya, biar murah biaya komunikasi,” katanya sambil terkekeh, ketawa yang sama persis seperti tujuh belas tahun lalu.
Di Bali, dia mempekerjakan sembilan orang. Ada yang membawa mobil boks, dan sebagian lain bermotor. Ia sendiri masih memasok dan menagih ke toko-toko kerajinan di pusat-pusat pelancongan di Bali. Nyaris semua toko sovenir memajang barangnya. Ia sendiri sudah punya satu toko yang dijaga empat orang.
Ia bekerja tanpa publikasi. Ia tak meminta bantuan dari pemerintah. Ia tak memasang iklan. Ia benar-benar telah menghubungkan pengrajin kecil di kampungnya, dengan pasar dan turis pengguna akhir dari apa yang diproduksi para pengrajin tersebut.
“Banyak pengrajin saya sudah pada naik haji. Saya aja yang belum. Pernah saya bercanda dengan mereka.Saya bilang ayo kumpul-kumpul uang dong, kalian ongkosin saya naik haji,” katanya.
Darinya saya tahu betapa mahal tanah di Denpasar. Ia sedang mencari satu lahan di tepi jalan besar untuk toko yang hendak ia bangun. Di toko itu nanti juga merangkap gudang – sekarang ruang rumahnya yang luas harus ia cadangkan sebagian untuk barang-barang dagangannya, itu sebabnya kepada saya ia menyebut bisnisnya, sebagai usaha rumahan - dan kamar-kamar cukup untuk semua orang yang bekerja padanya. “Kasihan, sewa kamar kos sekarang mahal. Saya sudah kasih mereka gaji bagus, tetap saja kalau saya hitung kurang. Kasihan,” katanya.
*
Hari ketika kami bertemu kemarin, dia berkali-kali menelepon dan menerima telepon sopir mobil boks yang berangkat membawa barang-barang dagangannya. Dari jam ke jam ia mengawasi sudah sampai mana perjalanan barang-barangnya tersebut. Sejumlah toko sudah kehabisan stok. Ia salah taksir. Bulan Juni tahun ini ternyata penjualan bagus sekali.
Sambil makan siang yang disiapkan istrinya – yang mengontrol pembukuan bisnis mereka - di rumahnya, saya melihat bagaimana seorang di negeri ini bekerja, tak merepotkan negara, tak mengemis pada pemerintah. Apa yang penting yang dapat saya pelajari dari kawan kuliah saya ini adalah: bisnis bisa dimulai dengan niat memberdayakan orang banyak. Kawan saya telah memberdayakan para pengrajin kecil di kampungnya.[]
Ia kenal dan dikenal dengan baik oleh kalangan bank di Bali. Ia nasabah yang baik, dan sudah banyak terima tawaran kredit. Ia tak pernah manfaatkan tawaran itu. Sebuah bank bahkan memberi fasilitas kredit siaga, sebesar Rp1 miliar. Dana sebesar itu dicatatkan atas namanya dan bisa dipakai kapanpun jika ia perlu. “Tak ada biaya, dan tak ada bunga.Kalau saya pakai, baru nanti kena bunga. Tapi, saya mau pakai buat apa?” katanya.
Pekan lalu dia menjemput saya di Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Ini pertemuan pertama kali setelah berpisah tujuh belas tahun lalu. Kami kuliah di universitas yang sama, angkatan sama, jurusan yang sama. Ia tergolong tekun, pintar, rajin, dan bersama beberapa kawan ia diwisuda lebih dahulu daripada rata-rata kami. Sejak itu kami tidak pernah bertemu. Secara fisik, ia tak banyak berubah. Ia pun tetap saja sederhana seperti saya mengenalnya dulu. Ponselnya dari kelas yang harganya tak sampai Rp200 ribu. Saya yang nyaris tak ia kenali. “Kamu gemuk,” katanya. Ya, tentu saja, di tahun-tahun kuliah saya menu tetap saya: tempe sayur sepotong, nasih putih, kecap yang banyak (gratis), dan lalap plus sambal (gratis). Harganya waktu itu Rp350.
Sewaktu kuliah dulu, bersama Yana – yang kini jadi istri saya - kami sama-sama mengelola majalah jurusan. Humus namanya. Nama yang diambil dari kuliah Dasar-dasar Ilmu Tanah. Humus adalah bentuk akhir dari pelapukan bahan organik, di mana mineral-mineralnya bisa diserap dengan mudah oleh tumbuhan. Humus, secara organik menyuburkan tanah.
Ada malam-malam kami habiskan di rental komputer, mengetik naskah untuk majalah dan menata perwajahan halaman-halamannya. Itu yang mengakrabkan kami. Ia berasal dari Tasik, dan sebagai orang Sunda yang baik dia tentu saja susah membedakan huruf dengan bunyi labial “p”, dan labiodental “v”, dan “f”. Ia pernah marah karena kami tertawa ketika dia bertanya, “Eh, ‘stap’ itu ngetiknya pakai ‘pe’ atau pakai ‘ep’?”
*
“Kerja di bank itu berat. Target tinggi,” katanya. Ia sempat berpindah kerja di dua bank swasta. Di bank kedua - ini yang ia syukuri - selama setahun lebih ia mendapat pelatihan soal seluk-beluk bisnis dan keuangan. Bagi kami yang dari Fakultas Pertanian, tentu itu ilmu baru.
Di bagian kredit, ia harus menyalurkan sejumlah besar dana nasabah. Targetnya gila-gilaan, katanya, tapi tetap saja itu harus dilakukan dengan sangat berhat-hati, sesuai azas kehati-hatian perbankan. “Berangkat kerja sudah stres. Mau sampai kantor tambah stres. Di kantor lebih stres lagi,” katanya.
Ia mulai berpikir membangun usahanya sendiri. Di kampungnya, banyak pengrajin barang-barang cindera mata yang pasarnya terbatas. Barangnya bagus-bagus. Desainnya khas. Dan jarang ada daerah lain yang memproduksi. Ia melihat peluang di situ. Ia berpikir untuk memasarkannya di tempat di mana arus turis tak putus sepanjang tahun: Bali.
“Saya mulai dulu pakai motor. Keranjang kiri kanan penuh sandal buatan Tasik,” katanya. Kalau saya ketemu dia saat itu, katanya, pasti saya tak percaya dan tak kenal. “Saya titip ke toko-toko, ke kios-kios di Sanur, Kuta, Denpasar,” katanya. Bali sama sekali asing buat dia. Ketika pertama kali mendengar dia ada di Bali, dan skala usahanya sudah besar, saya heran. Ketika bertemu, saya tanyakan itu. “Kok bisa terpikir berbisnis di Bali?” tanya saya. “Ya, coba-coba aja…” katanya.
Sepanjang perjalanan dari mobil ke rumahnya di kawasan Jimbaran, saya mengorek banyak pelajaran bisnis dari dia. Kawan saya ini menjaga hubungan sangat baik dengan pengrajin di kampungnya di Tasik. Ia menyeleksi dari beberapa, hingga sekarang punya tujuh kelompok pengrajin dengan jumlah pengraji tiga ratus orang lebih.
“Mereka saya minta hanya menyalurkan hasilnya hanya lewat saya. Beberapa desain dari saya, sesuai kebutuhan turis di Bali sini. Saya bayar kontan ke mereka.Uang saya kirim, mereka terima baru barang dikirim,” katanya.
Dengan cara itu, para pengrajin selalu punya dana untuk berproduksi. “Kalau ada yang minta pinjam uang untuk produksi, berarti ada yang tidak beres dari cara dia mengelola keuangan. Saya tak mau pakai lagi pengrajin yang begitu. Saya tahu berapa keuntungan mereka, dan berapa biaya produksi,” kata kawan saya. Ia dan para pengrajin memakai telepon selular dari satu operator yang sama. “Ini syarat penting kalau mau kerja sama dengan saya, biar murah biaya komunikasi,” katanya sambil terkekeh, ketawa yang sama persis seperti tujuh belas tahun lalu.
Di Bali, dia mempekerjakan sembilan orang. Ada yang membawa mobil boks, dan sebagian lain bermotor. Ia sendiri masih memasok dan menagih ke toko-toko kerajinan di pusat-pusat pelancongan di Bali. Nyaris semua toko sovenir memajang barangnya. Ia sendiri sudah punya satu toko yang dijaga empat orang.
Ia bekerja tanpa publikasi. Ia tak meminta bantuan dari pemerintah. Ia tak memasang iklan. Ia benar-benar telah menghubungkan pengrajin kecil di kampungnya, dengan pasar dan turis pengguna akhir dari apa yang diproduksi para pengrajin tersebut.
“Banyak pengrajin saya sudah pada naik haji. Saya aja yang belum. Pernah saya bercanda dengan mereka.Saya bilang ayo kumpul-kumpul uang dong, kalian ongkosin saya naik haji,” katanya.
Darinya saya tahu betapa mahal tanah di Denpasar. Ia sedang mencari satu lahan di tepi jalan besar untuk toko yang hendak ia bangun. Di toko itu nanti juga merangkap gudang – sekarang ruang rumahnya yang luas harus ia cadangkan sebagian untuk barang-barang dagangannya, itu sebabnya kepada saya ia menyebut bisnisnya, sebagai usaha rumahan - dan kamar-kamar cukup untuk semua orang yang bekerja padanya. “Kasihan, sewa kamar kos sekarang mahal. Saya sudah kasih mereka gaji bagus, tetap saja kalau saya hitung kurang. Kasihan,” katanya.
*
Hari ketika kami bertemu kemarin, dia berkali-kali menelepon dan menerima telepon sopir mobil boks yang berangkat membawa barang-barang dagangannya. Dari jam ke jam ia mengawasi sudah sampai mana perjalanan barang-barangnya tersebut. Sejumlah toko sudah kehabisan stok. Ia salah taksir. Bulan Juni tahun ini ternyata penjualan bagus sekali.
Sambil makan siang yang disiapkan istrinya – yang mengontrol pembukuan bisnis mereka - di rumahnya, saya melihat bagaimana seorang di negeri ini bekerja, tak merepotkan negara, tak mengemis pada pemerintah. Apa yang penting yang dapat saya pelajari dari kawan kuliah saya ini adalah: bisnis bisa dimulai dengan niat memberdayakan orang banyak. Kawan saya telah memberdayakan para pengrajin kecil di kampungnya.[]
Labels:
kolom
Monday, June 13, 2011
Di Teras Hotel Aston Denpasar
KAU bilang pantai itu harus berganti nama
Agar ombak yang tak pernah sama, tak bosan
datang ke sana, menyusup ke pasir, rahasia
Kau bukan bayang-bayang riang, berselancar
di gulungan api, membumbungkan kau tinggi
*
Kau datang bersama lelaki dari surga, yang
menciptakan untukmu surga, dan nanti juga
ia membawa kau, ke surga, yang dekat saja
Aku berterima kasih, untuk segigit legit,
padat kue brownie. Kita sepakati, inilah
sesajen untuk pertemanan yang sederhana
*
Kau sebut nama, alamat, seseorang bertempat
Dan buku-buku berbahasa asing menerjemahkan
halaman-halamannya sendiri, waktu kau curi
Agar ombak yang tak pernah sama, tak bosan
datang ke sana, menyusup ke pasir, rahasia
Kau bukan bayang-bayang riang, berselancar
di gulungan api, membumbungkan kau tinggi
*
Kau datang bersama lelaki dari surga, yang
menciptakan untukmu surga, dan nanti juga
ia membawa kau, ke surga, yang dekat saja
Aku berterima kasih, untuk segigit legit,
padat kue brownie. Kita sepakati, inilah
sesajen untuk pertemanan yang sederhana
*
Kau sebut nama, alamat, seseorang bertempat
Dan buku-buku berbahasa asing menerjemahkan
halaman-halamannya sendiri, waktu kau curi
Sunday, June 12, 2011
Kita Hanya Lewat di Ubud
DI Ubud kita hanya lewat, tidak makan, juga tidak berdoa. Tapi, kita sudah menemukan apa yang jauh dicari di naik perjalanan perempuan, dalam kisah yang diperankan oleh pelakon bermata awal musim semi, berambut rentang mayang pinang.
Sudah lama. Sejak sebelum kita hanya lewat di jalan-jalan sempit dan ramai ini. Yaitu ketika kau sisihkan tabungan untuk ongkos naik haji bagi sepasang orang tua. Lalu kau berdoa untuk keselamatannya, dalam dua kenduri yang berbeda lafaznya.
Sudah lama. Sejak sebelum kau tunjukkan sebarisan galeri perak, kedai lukisan, dan toko ukiran. Yaitu ketika kau rancang bangunan barak bagi pekerja, yang membuka lahan dan menanami bibit pohon hutan.
Di Ubud, ya, kita hanya lewat, di jalan sempit bersisian dengan pematang, berselisih dengan gembala bebek, dan gadis Jepang sedang lari-lari petang. Sawah-sawah, seperti tangan menadah, berdoa untuk - seasing apapun - siapa saja yang datang.
Sudah lama. Sejak sebelum kita hanya lewat di jalan-jalan sempit dan ramai ini. Yaitu ketika kau sisihkan tabungan untuk ongkos naik haji bagi sepasang orang tua. Lalu kau berdoa untuk keselamatannya, dalam dua kenduri yang berbeda lafaznya.
Sudah lama. Sejak sebelum kau tunjukkan sebarisan galeri perak, kedai lukisan, dan toko ukiran. Yaitu ketika kau rancang bangunan barak bagi pekerja, yang membuka lahan dan menanami bibit pohon hutan.
Di Ubud, ya, kita hanya lewat, di jalan sempit bersisian dengan pematang, berselisih dengan gembala bebek, dan gadis Jepang sedang lari-lari petang. Sawah-sawah, seperti tangan menadah, berdoa untuk - seasing apapun - siapa saja yang datang.
Bersama I Ketut Pasek di Bali
DEWA adalah petugas subak. Ia mengalirkan tawa dan waktu, ke sawahmu dan sawahku. Kita pejalan berkaki basah, berhati singgah
KITA ikan, menari di permukaan, menyelam hati dalam, sudah bertatap dengan mata air, di mana tangan Dewa mengada, menyejuk pada kita
DEWA dan kita, saling menjaga, di gerbang pura. Kita saling mendoa, pohon pinta, setinggi seribu kelapa
Awighnamastu
Amin
KITA ikan, menari di permukaan, menyelam hati dalam, sudah bertatap dengan mata air, di mana tangan Dewa mengada, menyejuk pada kita
DEWA dan kita, saling menjaga, di gerbang pura. Kita saling mendoa, pohon pinta, setinggi seribu kelapa
Awighnamastu
Amin
Saturday, June 11, 2011
Kitab Pertanyaan 61-66
Sajak Pablo Neruda
61
Apakah gugus Merkurius
terus berjatuhan ataukah ia abadi?
Apakah puisi nestapaku
menatap dengan mataku sendiri?
Akankah tetap ada aromaku dan pedihku
ketika, terhancurkan, tidur kuteruskan?
62
Apa artinya bertahan
di lorong kematian?
Bagaimanakah gurun garam itu
mungkinkah ia mekar di sana?
Di laut dimana tak terjadi apa-apa,
adakah pakaian untuk berlagak bak mati?
Kini tulang-belulang tak ada lagi
siapa yang hidup di debu penghabisan?
63
Bagaimanakah burung-burung mengatur
terjemahan di antara bahasa-bahasa mereka?
Bagaimana aku memberi tahu kura-kura
bahwa aku lebih lamban daripada dia?
Bagaimana aku meminta pada kutuanjing
catatan kemenangannya?
Bagaimana juga aku memberi tahu anyelir
bahwa aku berterima kasih untuk wanginya?
64
Mengapa bajukk yang mengusam
berkibar seperti bendera?
Apakah aku ini kadang-kadang jahat
atau aku selalu baik berbudi?
Apakah kita belajar kebaikan hati,
atau sekadar topeng kebaikan?
Apakah perdu mawar kejahatan itu putih
dan bukankah bunga kebaikan itu hitam?
Siapa memberi nama dan nomor
kepada kepolosan yang tak berangka?
65
Apakah jatuhan serpih logam bercahaya
seperti suku kata dalam laguku?
Apakah kata kadang-kadang
melata seperti ular naga?
Bukankah nama seperti oranye
mengendap menuju jantungmu?
Dari sungai manakah ikan datang?
Apakah dari kata pengrajin perak?
Ketika diselinapkan terlalu banyak huruf hidup
tidakkah kapal layak jadi karam?
66
Apakah huruf O pada kata lokomotif
meloloskan asap, api atau uap?
Dalam bahasa apakah hujan yang curah
di kota-kota yang sengsara?
Di waktu fajar, suku kata lembut apa,
udara samudera menyebut ulang?
Adakah bintang yang lebih terbuka
daripada kata popi?
Adakah dua taring yang lebih tajam
daripada suku kata serigala?
61
Apakah gugus Merkurius
terus berjatuhan ataukah ia abadi?
Apakah puisi nestapaku
menatap dengan mataku sendiri?
Akankah tetap ada aromaku dan pedihku
ketika, terhancurkan, tidur kuteruskan?
62
Apa artinya bertahan
di lorong kematian?
Bagaimanakah gurun garam itu
mungkinkah ia mekar di sana?
Di laut dimana tak terjadi apa-apa,
adakah pakaian untuk berlagak bak mati?
Kini tulang-belulang tak ada lagi
siapa yang hidup di debu penghabisan?
63
Bagaimanakah burung-burung mengatur
terjemahan di antara bahasa-bahasa mereka?
Bagaimana aku memberi tahu kura-kura
bahwa aku lebih lamban daripada dia?
Bagaimana aku meminta pada kutuanjing
catatan kemenangannya?
Bagaimana juga aku memberi tahu anyelir
bahwa aku berterima kasih untuk wanginya?
64
Mengapa bajukk yang mengusam
berkibar seperti bendera?
Apakah aku ini kadang-kadang jahat
atau aku selalu baik berbudi?
Apakah kita belajar kebaikan hati,
atau sekadar topeng kebaikan?
Apakah perdu mawar kejahatan itu putih
dan bukankah bunga kebaikan itu hitam?
Siapa memberi nama dan nomor
kepada kepolosan yang tak berangka?
65
Apakah jatuhan serpih logam bercahaya
seperti suku kata dalam laguku?
Apakah kata kadang-kadang
melata seperti ular naga?
Bukankah nama seperti oranye
mengendap menuju jantungmu?
Dari sungai manakah ikan datang?
Apakah dari kata pengrajin perak?
Ketika diselinapkan terlalu banyak huruf hidup
tidakkah kapal layak jadi karam?
66
Apakah huruf O pada kata lokomotif
meloloskan asap, api atau uap?
Dalam bahasa apakah hujan yang curah
di kota-kota yang sengsara?
Di waktu fajar, suku kata lembut apa,
udara samudera menyebut ulang?
Adakah bintang yang lebih terbuka
daripada kata popi?
Adakah dua taring yang lebih tajam
daripada suku kata serigala?
Friday, June 10, 2011
Kitab Pertanyaan 21-30
Sajak Pablo Neruda
21
Dan ketika cahaya ditempa
apakah itu terjadi di Venezuela?
Di manakah pusat lautan?
Kenapa ombak tak menuju ke sana?
Benarkah itu, bahwa meteor
adalah merpati dari batu ametis?
Bolehkah aku bertanya pada bukuku
apakah aku telah menulisnya dengan benar?
22
Cinta, cinta, pada lelaki dan perempuan
kalau ia tak lagi ada, kemana dia pergi?
Kemarin, kemarin, aku tanya matakku
kapan kami saling bertatapan lagi?
Dan ketika kau mengubah lansekap
dengan tangan telanjangkah atau sarung tangan?
Bagaimana rumok tercium di langit
ketika air yang biru berlagu?
23
Jika kupu-kupu terus bertransmogrifi
apakah dia akan berubah jadi ikan terbang?
Maka, tidak benar bukan
jika ada yang mengatakan Tuhan tinggal di bulan?
Apa warna aroma
isak tangis biru bunga violeta?
Berapa pekankah ada dalam hari sehari
dan berapa tahunkah ada dalam bulan sebulan?
24
Apakah empat sama dengan empat bagi semua orang?
Apakah semua tujuh itu sama jumlahnya?
Ketika si terhukum merenungkan cahaya
Apakah itu cahaya yang sama menyinari engkau?
Coba kau pikir, apa warna April
ketika ia terjangkit penyakit?
Monarki oksidental manakah
yang akan mengibarkan bendera bunga popi?
25
Kenapa pepohonan itu melepaskan bajunya sendiri
hanya untuk menunggu datangnya salju?
Dan bagaimana kita tahu manakah Dewa
di antara banyak Dewa di Kalkuta?
Kenapa semua ulat sutera
hidup dengan pakaian compang-camping?
Kenapa ia susah sekali, kemanisan
hati buah ceri?
Apakah karena ia harus mati
atau karena hidup harus terus dihidupkan?
26
Apakah senator yang berkhidmat
yang mempersembahkan sebuah kuil untukku
sudah melahap, dengan kemenakannya,
kue pembantaian?
Siapa yang dikecoh oleh magnolia
dengan aroma limaunya itu?
Dimanakah elang meletakkan belatinya
ketika ia hinggap di awan?
27
Mungkin mereka mati karena malu
kereta api yang tersesat jalan?
Siapa yang tak pernah melihat pahit lidabuaya?
Di manakah mereka menanam,
mata kamerad Paul Eluard?
Apakah engkau punya ruang untuk duri?
Mereka bertanya kepada perdu mawar.
28
Kenapa orang yang tua tak ingat
pada hutang dan lepuh luka bakar?
Apakah itu nyata, aroma
gadis yang terkejut, gadis yang perawan
Kenapasi fakir tak mengerti
secepat mereka berhenti menjadi fakir?
Di mana engkau bisa temukan lonceng
yang berdentang dalam mimpimu?
29
Berapa jarak dalam kisaran meter
antara matahari dan jeruk oranye?
Siapa yang membangunkan matahari
yang sedang tidur di ranjang berapinya?
Apakah bumi bernyanyi seperti jengkerik
dengan alun musik dari surga?
Apakah benar duka itu tebal
dan melankoli itu tipis?
30
Ketika menulis buku birunya
apakah Ruben Dario menghijau?
Bukankah Rimbaud merah kelam,
Gongora ungu teduh?
Apakah semua kenangan si fakir
berjubal bersama di kampung itu?
Dan apakah si kaya menjaga mimpinya
di kotak ukiran dari mineral?
21
Dan ketika cahaya ditempa
apakah itu terjadi di Venezuela?
Di manakah pusat lautan?
Kenapa ombak tak menuju ke sana?
Benarkah itu, bahwa meteor
adalah merpati dari batu ametis?
Bolehkah aku bertanya pada bukuku
apakah aku telah menulisnya dengan benar?
22
Cinta, cinta, pada lelaki dan perempuan
kalau ia tak lagi ada, kemana dia pergi?
Kemarin, kemarin, aku tanya matakku
kapan kami saling bertatapan lagi?
Dan ketika kau mengubah lansekap
dengan tangan telanjangkah atau sarung tangan?
Bagaimana rumok tercium di langit
ketika air yang biru berlagu?
23
Jika kupu-kupu terus bertransmogrifi
apakah dia akan berubah jadi ikan terbang?
Maka, tidak benar bukan
jika ada yang mengatakan Tuhan tinggal di bulan?
Apa warna aroma
isak tangis biru bunga violeta?
Berapa pekankah ada dalam hari sehari
dan berapa tahunkah ada dalam bulan sebulan?
24
Apakah empat sama dengan empat bagi semua orang?
Apakah semua tujuh itu sama jumlahnya?
Ketika si terhukum merenungkan cahaya
Apakah itu cahaya yang sama menyinari engkau?
Coba kau pikir, apa warna April
ketika ia terjangkit penyakit?
Monarki oksidental manakah
yang akan mengibarkan bendera bunga popi?
25
Kenapa pepohonan itu melepaskan bajunya sendiri
hanya untuk menunggu datangnya salju?
Dan bagaimana kita tahu manakah Dewa
di antara banyak Dewa di Kalkuta?
Kenapa semua ulat sutera
hidup dengan pakaian compang-camping?
Kenapa ia susah sekali, kemanisan
hati buah ceri?
Apakah karena ia harus mati
atau karena hidup harus terus dihidupkan?
26
Apakah senator yang berkhidmat
yang mempersembahkan sebuah kuil untukku
sudah melahap, dengan kemenakannya,
kue pembantaian?
Siapa yang dikecoh oleh magnolia
dengan aroma limaunya itu?
Dimanakah elang meletakkan belatinya
ketika ia hinggap di awan?
27
Mungkin mereka mati karena malu
kereta api yang tersesat jalan?
Siapa yang tak pernah melihat pahit lidabuaya?
Di manakah mereka menanam,
mata kamerad Paul Eluard?
Apakah engkau punya ruang untuk duri?
Mereka bertanya kepada perdu mawar.
28
Kenapa orang yang tua tak ingat
pada hutang dan lepuh luka bakar?
Apakah itu nyata, aroma
gadis yang terkejut, gadis yang perawan
Kenapasi fakir tak mengerti
secepat mereka berhenti menjadi fakir?
Di mana engkau bisa temukan lonceng
yang berdentang dalam mimpimu?
29
Berapa jarak dalam kisaran meter
antara matahari dan jeruk oranye?
Siapa yang membangunkan matahari
yang sedang tidur di ranjang berapinya?
Apakah bumi bernyanyi seperti jengkerik
dengan alun musik dari surga?
Apakah benar duka itu tebal
dan melankoli itu tipis?
30
Ketika menulis buku birunya
apakah Ruben Dario menghijau?
Bukankah Rimbaud merah kelam,
Gongora ungu teduh?
Apakah semua kenangan si fakir
berjubal bersama di kampung itu?
Dan apakah si kaya menjaga mimpinya
di kotak ukiran dari mineral?
Thursday, June 9, 2011
Kitab Pertanyaan 51-60
Sajak Pablo Neruda
51
Kenapa aku membenci kota-kota
beraroma perempuan dan bau pesing?
Bukankah kota itu samudera
gemetar hampar tilam?
Bukankah angin-angin Oceania
mereka punya pulau dan pohon palma?
Kenapa aku kembali ke laut yang sama
laut yang tak berbatasan?
52
Berapa besarkah gurita hitam itu
yang mengelamkan kedamaian hari?
Apakah lengannya itu terbuat dari besi
dan matanya, api yang mati?
Dan kenapa ikan paus tiga warna
mencampakkan aku di jalanan?
53
Siapa yang rakus di hadapanku itu
seekor hiu penuh jerawat?
Siapa yang bersalah, badai yang tiba-tiba
ataukah ikan berlumur darah?
Apakah ini hempas ombak berterusan
mengacak urutan atau sebuah pertempuran?
54
Benarkah bahwa burung layang-layang itu
mereka hendak bermukim di bulan?
Apakah mereka akan membawa musim semi
merobeknya dari kornisa
Apakah burung layang-layang bulan itu
akan pulang di musim gugur
Apalah mereka mematuki langit
mencari serpih jejak mineral bismut
Dan apakah mereka akan hinggap lagi
di balkon dengan bulu berlumur abu?
55
Kenapa mereka tidak mengirim tikus mondok
atau kura-kura saja ke bulan sana?
Dapatkah binatang yang pandai
membuat rongga dan lorong
mengambil alih tugas-tugas
penilikan di jarak kejauhan ini?
56
Engkau tak percaya bahwa unta
itu menyimpan bulan di punuknya?
Tidakkah mereka menaburkannya di gurun
dengan ketekunan rahasia?
Dan bukankah laut itu dipinjamkan
sebentar saja kepada bumi?
Maukah kita mengembalikannya
bersama pasang airnya kepada bulan?
57
Bukankah akan baik sekali, mengacaukan
aturan, antarplanet berkecupan?
Siapa yang tak meneliti ini sebelum
menyelaraskan dengan planet lain
Dan kenapa tidak platipus saja
yang berpakaian untuk antariksa?
Kenapa tapal kuda tidak dibuat
untuk kuda-kuda berjalan di bulan?
58
Dan apa yang menghentak di malam itu?
Apakah itu planet atau derap tapal kuda?
Pagi ini haruskah aku memilih
antara laut telanjang atau langit?
Dan kenapa langit itu mengenakan gaun
terlalu lekas di halimun pagi ini?
Apakah yang menunggu aku di Isla Negra?
Kebenaran hijau atau kepantasan?
59
Kenapa aku tidak dilahirkan misterius saja?
Kenapa aku tidak tumbuh tanpa kawan saja?
Siapa yang meminta aku merayapi bumi
pintu harga diriku sendiri?
Dan siapa yang keluar dari diriku untukku
ketika aku tidur atau sakit?
Dan bendera apa yang membentang di sana
di mana mereka tak melupakan aku?
60
Dan apa perlunya aku harus berada
di ruang sidang yang dilupakan?
Manakah gambaran yang benar tentang
bagaimana masa depan tampak-menjelang?
Apakah itu benih pepadian
di antara tumpukan jerami kuning itu?
Atau itu adalah tulang jantung
yang diutus oleh buah persik?
Friday, June 3, 2011
Satu-satunya Alinea yang Bisa Kaubaca dari Sekian Alinea yang Ingin Kutulis
SUDAH aku bersihkan gulma. Rasa liar yang menghama. Hatiku, bukan lagu huma. Sudah aku sisihkan batu. Melilip di gerutu mata garu. Aku tak bisa pergi dari situ, tapi tak lagi menunggu. Sudah aku mandikan, diri yang badan, dengan parah harapan, pada hujan masih membasahkan.
Tetapi Tidak, Taipei!
TETAPI, Taipei bilang tidak pada dia, lelaki yang berdiri, diri ia jagai.
Tak berkedip, menatap sejarah: mengering itu darah. Sesudah sudah?
Tetapi, Taipei cium tangan Waktu, apa yang tak termuseumkan itu
Tetapi, Taipei bilang tidak pada lelaki terburu, ke gedung berlantai
Tetapi, Taipei cium tangan Waktu, apa yang tak termuseumkan itu
Tetapi, Taipei bilang tidak pada lelaki terburu, ke gedung berlantai
dua puluh entah itu. Ia menyebut sepatah kata yang patah, dari situ
Tumbuh sayap: dua belah, lalu ia terbanglah. Tinggi. Tinggi sekali
Tetapi, Taipei bilang tidak pada dia lelaki berpeluh baju, membajak
Tetapi, Taipei bilang tidak pada dia lelaki berpeluh baju, membajak
Subscribe to:
Comments (Atom)